Pagi ini saya menerima pesan dari seorang teman di Instagram yang sedang mempersiapkan diri melamar beasiswa S3. Ia bertanya: ‘Bagaimana cara menulis proposal disertasi yang kuat?’
Melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral adalah impian banyak akademisi dan peneliti muda di Indonesia. Jalan menuju jenjang ini tidak hanya menuntut kesiapan akademik, namun juga kelengkapan administratif dan strategi komunikasi ilmiah yang matang. Salah satu tahapan penting yang menjadi gerbang awal dalam proses seleksi beasiswa S3, baik dari LPDP, BPI Kemendikbudristek, maupun PDDI, adalah penyusunan proposal penelitian. Proposal ini bukan sekadar prasyarat formal, melainkan cerminan dari kapasitas intelektual pelamar dan arah kontribusi keilmuannya ke depan.
1. Memahami karakter lembaga beasiswa dan menyesuaikan arah riset.
Ketika kita mulai menyusun proposal untuk keperluan beasiswa, hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa setiap lembaga pendana memiliki karakter dan orientasi strategisnya masing-masing. LPDP, misalnya, sangat menekankan aspek kontribusi terhadap pembangunan nasional, penguatan kapasitas kepemimpinan, dan kesinambungan dampak sosial dari studi yang ditempuh. BPI Kemendikbudristek/ sekarang namanya PDDI Kemendiktisaintek lebih terfokus pada penguatan kapasitas SDM perguruan tinggi dan dukungan terhadap tridharma, terutama bagi dosen. Maka, memahami arah kebijakan dan misi institusi pendana adalah pijakan awal yang fundamental. Tanpa pemahaman ini, proposal berisiko menjadi dokumen lepas konteks, seakan-akan berdiri di ruang akademik yang vakum.
2. Menentukan topik yang strategis dan relevan.
Topik yang kita pilih untuk diteliti semestinya tidak semata didasarkan pada minat pribadi. Ia harus berada di persimpangan antara ketertarikan intelektual, kebutuhan empiris di masyarakat, dan prioritas ilmu pengetahuan yang sedang berkembang. Dalam konteks Indonesia, topik yang menyentuh isu pendidikan inklusif, kesehatan reproduksi remaja, teknologi pembelajaran digital, atau pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal, seringkali mendapat perhatian karena menyentuh dimensi pembangunan yang urgen dan kompleks. Di sinilah peran kita sebagai calon peneliti S3: merumuskan masalah yang bukan hanya ilmiah secara konseptual, tetapi juga strategis secara kebijakan. Misalnya, saat meneliti literasi digital di daerah 3T, kita bukan hanya mengkaji kemampuan individu mengakses teknologi, tapi juga bagaimana literasi tersebut berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga dan keberlanjutan pendidikan anak.
3. Menyusun struktur proposal yang utuh dan naratif.
Dalam menulis proposal, struktur dokumen menjadi penting sebagai kerangka berpikir kita. Namun lebih dari sekadar struktur, adalah bagaimana setiap bagian saling menjalin narasi yang logis, utuh, dan koheren. Kita mulai dengan latar belakang, yang bukan hanya menjelaskan permasalahan, tetapi juga menyusun kerangka logika dari fenomena umum ke kasus yang spesifik. Pada bagian ini, keberadaan data empiris, baik kuantitatif maupun kualitatif, serta rujukan dari studi-studi sebelumnya sangat penting untuk meyakinkan pembaca bahwa isu yang diangkat benar-benar aktual, relevan, dan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa proposal tidak dibangun dari asumsi pribadi semata, melainkan dari kenyataan lapangan yang dapat diverifikasi secara ilmiah. Saran saya, baca dan pedomani struktur proposal setiap lembaga penyandang dana beasiswa.
4. Menyusun latar belakang, rumusan masalah dan Kelogisan (Rationale)
Latar Belakang: "Uraikan secara singkat topik isu yang ingin Anda meneliti dan mengapa signifikan untuk Anda teliti."
Dalam menyusun proposal riset doktoral, bagian latar belakang memegang peran penting dalam memperkenalkan konteks topik yang akan diteliti serta menunjukkan signifikansinya. Latar belakang bukan hanya menjelaskan bahwa suatu masalah ada, tetapi harus menyampaikan mengapa isu tersebut penting untuk diteliti dan relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau pemecahan masalah aktual. Oleh karena itu, penyusunan latar belakang sebaiknya dimulai dengan paparan umum fenomena yang terjadi, kemudian dipersempit hingga mengarah pada fokus persoalan yang menjadi inti penelitian.
Dalam mendukung penjabaran tersebut, sangat dianjurkan untuk menyertakan bukti empiris baik dari data kuantitatif maupun temuan kualitatif. Keduanya menunjukkan bahwa permasalahan yang diangkat tidak hanya berdasarkan asumsi pribadi, melainkan nyata terjadi di lapangan dan tercermin dalam berbagai studi sebelumnya. Bukti ini tidak harus selalu berupa statistik, melainkan dapat berupa hasil wawancara terdahulu, pengamatan, atau studi literatur yang relevan dan mutakhir. Dengan demikian, bagian latar belakang sekaligus menjadi fondasi logis bagi perumusan masalah penelitian.
Rumusan Masalah "Uraikan secara singkat apa yang telah Anda ketahui tentang topik isu tersebut dan diskusikan secara ringkas mengapa masih perlunya Anda meneliti. Tunjukkan bahwa solusi terhadap isu yang telah ada masih belum terselesaikan sepenuhnya sehingga Anda ingin melakuan penelitian."
Pada bagian Statement of Problem, penulis perlu menunjukkan kesenjangan (gap) yang jelas antara pengetahuan atau pemahaman yang telah ada dengan kondisi aktual yang belum terpecahkan. Penting untuk menjelaskan secara ringkas apa yang telah diketahui dari hasil studi sebelumnya, lalu menunjukkan area mana yang belum dijelajahi atau belum sepenuhnya terselesaikan. Di sinilah urgensi penelitian ditegaskan, sekaligus menjawab pertanyaan: mengapa penelitian ini penting dilakukan saat ini? Rumusan masalah yang tajam dan relevan akan memperkuat posisi riset yang diusulkan sebagai kontribusi orisinal terhadap disiplin ilmu tertentu.
Kelogisan
"Jelaskan bagaimana pertanyaan penelitian mendukung topik isu besar yang diangkat dalam latar belakang penelitian. Khusus penelitian, jelaskan hipotesis (jika ada) dan/atau model penelitian yang mendukung tujuan/pertanyaan penelitian. Jelaskan pula kontribusi teoritis dan praktis jika hipotesis tidak terbukti."
Dari rumusan masalah tadi diturunkan pertanyaan penelitian yang spesifik, serta tujuan penelitian yang bersifat operasional. Pertanyaan penelitian tersebut harus selaras dengan isu besar yang telah diuraikan dalam latar belakang, dan menjadi benang merah yang menjembatani antara konteks masalah dengan upaya pemecahannya. Dalam konteks penelitian tertentu, penting juga untuk mencantumkan hipotesis (jika ada), atau model konseptual yang mendukung arah pencarian jawaban ilmiah. Bahkan bila hipotesis nantinya tidak terbukti, penelitian tetap harus memiliki kontribusi yang signifikan, baik dalam memperkuat teori yang ada, menawarkan alternatif pendekatan, maupun memberikan wawasan baru bagi praktik kebijakan atau pengembangan program di lapangan. Kesalahan umum dalam tahap ini adalah membuat rumusan masalah yang terlalu umum, terlalu banyak, atau tidak memiliki benang merah dengan kerangka metodologis.
Sebagai contoh, Kelogisan dalam bidang energi :
"Pengembangan energi terbarukan dan eksplorasi sumber energi baru dari biogas merupakan fokus strategis Indonesia dalam rangka menjawab tantangan ketahanan energi dan keberlanjutan lingkungan. Keterampilan riset yang akan saya peroleh melalui studi doktoral di University of Sheffield, Inggris, akan memperkuat kapasitas saya dalam mengembangkan bidang ini secara lebih mendalam dan sistematis. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pengembangan teknologi biogas yang lebih efisien dan aplikatif di Indonesia, serta berkontribusi dalam penguatan kebijakan energi nasional berbasis sumber daya lokal."
Contoh dalam bidang pendidikan bahasa:
Peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya dalam hal literasi membaca dan menulis, menjadi fokus penting dalam penguatan karakter dan kompetensi siswa di era Kurikulum Merdeka. Rendahnya kemampuan literasi siswa, sebagaimana tercermin dalam hasil asesmen nasional dan studi internasional seperti PISA, menunjukkan bahwa pendekatan pengajaran Bahasa Indonesia di sekolah perlu ditinjau kembali secara lebih kritis dan kontekstual.
Melalui studi doktoral di bidang Pendidikan Bahasa Indonesia, saya berharap dapat mengembangkan model pembelajaran inovatif berbasis teks multimodal yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan temuan empiris yang memperkuat efektivitas pembelajaran berbasis konteks, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pedagogi literasi kritis di tingkat nasional. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembelajaran Bahasa Indonesia yang lebih transformatif, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan literasi global.
5. Menyusun tujuan, manfaat, dan kontribusi ilmiah.
"Deskripsikan secara umum, bagaimana penelitian yang Anda usulkan berguna baik secara teoritis maupun praktis."
Pada tahap tujuan dan manfaat, kita perlu menyampaikan dengan bahasa yang ringkas namun padat makna. Tujuan penelitian harus langsung menjawab rumusan masalah, tanpa menyimpang atau menambah elemen yang tidak relevan. Sementara manfaat sebaiknya dijelaskan dalam tiga dimensi: manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat kebijakan. Apabila penelitian kita dirancang dengan mempertimbangkan dampak pada pengembangan kebijakan nasional atau pemecahan masalah komunitas tertentu, maka manfaat tersebut harus ditekankan dengan narasi yang konkret.
6. Menjelaskan metodologi secara operasional dan meyakinkan.
"Jelaskan bagaimana Anda akan mengumpulkan data dan mengapa. Jelaskan mengapa metode ini adalah terbaik untuk mencapai tujuan Anda. Jelaskan analisis dan hasil yang mendukung maupun tidak mendukung hipotesis. Cantumkan outline jadwal penelitian dari awal sampai selesai."
Salah satu bagian paling kritis dalam proposal adalah metodologi penelitian. Di sinilah banyak pelamar beasiswa gagal meyakinkan reviewer. Metodologi bukan hanya sekadar menyebutkan “penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus”, namun harus dijabarkan secara rinci. Kita harus menjelaskan siapa subjek penelitian, bagaimana teknik pengambilan data dilakukan, seperti apa instrumen yang digunakan, serta bagaimana data akan dianalisis. Selain itu, proposal yang baik juga menunjukkan bahwa peneliti paham betul keterbatasan dan tantangan dari pendekatan yang digunakan. Misalnya, jika menggunakan metode kualitatif, perlu dijelaskan bagaimana kredibilitas dan validitas data dijaga. Jika menggunakan pendekatan kuantitatif, bagaimana teknik sampling dan pengujian hipotesis akan dilakukan harus dijelaskan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh pembaca lintas bidang.
Outline Jadwal Penelitian
Outline Jadwal penelitian selama studi doktoral juga menjadi bagian yang penting dalam proposal. Meskipun bersifat proyeksi, penyusunan jadwal ini menunjukkan bahwa pelamar memiliki kesadaran waktu, perencanaan yang matang, dan tidak akan menyelesaikan disertasinya dalam cara yang acak. Biasanya, tahun pertama dialokasikan untuk peninjauan literatur dan penyusunan instrumen, tahun kedua untuk pengumpulan data, tahun ketiga untuk analisis dan penulisan, dan tahun keempat untuk diseminasi serta publikasi. Jika pelamar sudah memiliki gambaran akan menulis di jurnal internasional tertentu atau terlibat dalam forum akademik tertentu, hal ini sebaiknya dicantumkan karena menunjukkan kesiapan akademik yang lebih tinggi.
Penyesuaian outline studi doktoral (S3) dengan kalender akademik Indonesia sangat penting untuk memastikan kesinambungan antara aktivitas riset dengan jadwal perkuliahan, kegiatan akademik, serta evaluasi administrasi seperti laporan kemajuan dan promosi doktor. Dalam konteks ini, kalender akademik yang dimulai pada bulan Agustus atau September menjadi dasar penyusunan alur penelitian selama tiga tahun masa studi. Buat dalam bentuk tabel.
Pada tahun pertama, kegiatan difokuskan pada studi literatur yang intensif dan penajaman fokus riset. Aktivitas ini berlangsung sejak awal perkuliahan, yakni bulan Agustus hingga November. Dalam periode tersebut, mahasiswa juga mempersiapkan penyusunan proposal disertasi yang akan diseminarkan sebagai salah satu tonggak penting awal studi. Setelah proposal diseminarkan, kegiatan dilanjutkan dengan pengembangan instrumen penelitian dan proses validasi, yang biasanya berlangsung dari Desember hingga pertengahan tahun kedua (sekitar bulan Juni). Masa ini juga menjadi waktu untuk menyelesaikan berbagai perizinan lapangan serta uji coba instrumen.
Tahun kedua merupakan periode paling intens dalam pelaksanaan riset. Pengumpulan data utama dilakukan sejak bulan Juli hingga Maret, tergantung pada pendekatan penelitian yang digunakan—baik itu survei, wawancara mendalam, observasi lapangan, maupun eksperimen. Setelah seluruh data terkumpul, peneliti melanjutkan ke tahap pengolahan awal dan transkripsi data yang umumnya dilakukan pada bulan April hingga Mei. Tahapan ini krusial untuk memastikan kualitas dan kelengkapan data sebelum masuk ke analisis mendalam.
Memasuki tahun ketiga, fokus berpindah ke proses analisis data dan penyusunan laporan disertasi. Aktivitas ini biasanya dimulai dari bulan Juni hingga Oktober. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk draf disertasi yang siap dipresentasikan dalam seminar hasil. Selain seminar, tahun terakhir juga menjadi momentum strategis untuk menyiapkan publikasi ilmiah, baik di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. Pada semester akhir, yakni November hingga Juli, mahasiswa diharapkan sudah siap menjalani ujian promosi doktor.
Pada tahun ketiga pula, kegiatan penulisan artikel ilmiah mulai difokuskan. Artikel pertama umumnya ditulis berdasarkan hasil temuan utama dari data yang telah dianalisis dan ditargetkan untuk jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi menengah. Penulisan dilakukan paralel dengan penyusunan disertasi agar hasilnya saling mendukung. Artikel kedua atau artikel lanjutan dapat difokuskan pada aspek teoretis, metodologis, atau studi kasus dari riset utama, dan ditargetkan untuk jurnal internasional bereputasi tinggi. Idealnya, artikel pertama selesai dalam rentang Januari hingga April tahun ketiga, dan artikel kedua ditulis serta dikirim antara Mei hingga Oktober, sehingga mahasiswa masih memiliki waktu untuk revisi, seminar hasil, dan penyelesaian promosi doktor.
Keseluruhan struktur waktu ini dirancang agar terintegrasi secara optimal dengan sistem akademik perguruan tinggi di Indonesia. Namun, timeline tersebut tetap fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kompleksitas riset, regulasi kampus, serta peluang kolaborasi riset di dalam maupun luar negeri. Dengan penyusunan timeline yang matang dan terstruktur, proses studi S3 diharapkan berjalan efektif dan efisien menuju penyelesaian tepat waktu.
7. Kebaruan dan Kontribusi
Yang tak kalah penting adalah menyusun narasi kebaruan dan kontribusi. Reviewer ingin tahu: apa yang membuat riset ini berbeda? Apakah ada pendekatan baru? Populasi yang unik? Kombinasi teori yang belum pernah digunakan sebelumnya? Atau kemungkinan hasil riset ini untuk diadopsi secara luas oleh pembuat kebijakan atau pelaku di lapangan? Argumentasi novelty ini harus dibangun secara logis dan tidak dibuat-buat. Jika memungkinkan, kita bisa menyebutkan bahwa belum ada penelitian serupa di Indonesia, atau bahwa riset ini merespons tantangan kontemporer yang belum tertangani secara optimal oleh pendekatan konvensional.
8. Menghindari kesalahan umum dalam penulisan proposal.
Ada pula beberapa kesalahan yang harus dihindari. Proposal yang asal salin dari skripsi atau tesis jelas akan mudah dikenali dan dianggap tidak orisinal. Demikian juga, proposal yang tidak mencantumkan landasan teori atau kerangka konseptual akan dianggap tidak matang. Tidak sedikit pula pelamar yang menggunakan referensi lama atau bahkan tidak menyertakan referensi sama sekali, padahal ini akan melemahkan argumen dan menunjukkan bahwa pelamar kurang terlibat dalam diskusi akademik terkini.
9. Menyertakan dokumen pendukung dan personal statement yang kuat.
Di luar isi proposal, keberhasilan aplikasi beasiswa juga ditentukan oleh kesiapan dokumen pendukung lainnya. Surat rekomendasi dari dosen pembimbing atau calon promotor yang mengenal kita secara akademik sangat penting. Demikian pula, personal statement yang kuat, yang mencerminkan motivasi, perjalanan intelektual, dan visi masa depan, akan memperkuat impresi reviewer terhadap keseluruhan berkas. Jika kita memiliki pengalaman riset, publikasi, atau keterlibatan dalam proyek sosial, hal-hal ini dapat disebutkan untuk membangun narasi integritas dan komitmen kita terhadap ilmu dan masyarakat.
Baca juga: Rahasia Menulis Personal Statemen yang Tidak Membosankan
Akhirnya, menyusun proposal bukan hanya soal menjawab formulir beasiswa. Ia adalah pernyataan komitmen akademik, sebuah janji untuk menempuh jalan panjang dengan dedikasi terhadap ilmu pengetahuan, dan harapan akan kontribusi nyata untuk bangsa. Menulis proposal bukanlah pekerjaan satu malam, tapi sebuah proses refleksi dan perumusan diri sebagai ilmuwan masa depan. Maka, luangkan waktu, konsultasikan dengan mentor atau dosen, dan perbaiki proposal secara bertahap. Jangan segan untuk menguji argumen kita kepada orang lain, menerima kritik, dan merevisi berkali-kali. Walaupun pada akhirnya, bisa saja proposalnya berubah saat kuliah😊.
Beasiswa S3 adalah investasi jangka panjang. Bagi pemberi beasiswa, proposal kita adalah bukti awal bahwa investasi mereka akan menghasilkan individu yang mampu berpikir tajam, bekerja tuntas, dan berkontribusi nyata. Maka, tulislah proposal bukan sekadar untuk lulus seleksi, tetapi untuk memulai sebuah transformasi intelektual dan sosial yang lebih luas.
Malang, 21 Dzulhijjah 1446 H
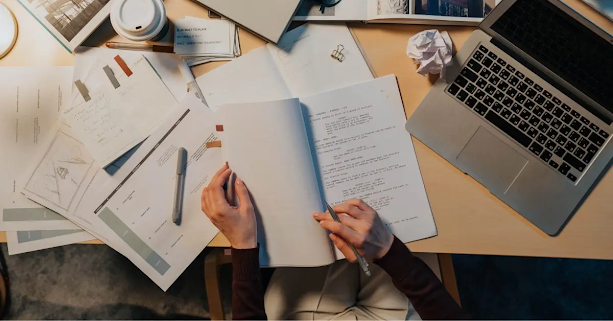
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih telah berkunjung. Semoga langkah Anda hari ini membawa semangat baru untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Saya menghargai setiap dedikasi dan perjalanan Anda. Sampai kita berjumpa kembali, dalam tulisan atau kehidupan nyata.